Apakah Buah Mangrove Termaktub dalam Ayat Saba 16 dalam Al-Qur'an?
Apakah Buah Mangrove Termaktub dalam Ayat Saba 16 dalam Al-Qur'an?
Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita analisis terlebih dahulu isi Surah Saba ayat 16 dalam Al-Qur'an, kemudian menghubungkannya dengan konteks buah mangrove dan potensi pangan di wilayah pesisir Indonesia.Teks dan Tafsir Surah Saba Ayat 16Surah Saba ayat 16 berbunyi:
"Fa a‘radū fa arsalnā ‘alaihim sailal-‘arim wa baddalnāhum bi jannatayhim jannataini dzawātai ukulin khamthin wa aslin wa syai’in min sidrin qalīl."
Terjemahan dalam bahasa Indonesia (Kementerian Agama RI):
"Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon-pohon atsar, dan sedikit pohon bidara."
Ayat ini menceritakan kisah kaum Saba di Yaman yang awalnya hidup makmur dengan dua kebun subur berkat bendungan Ma'rib. Namun, karena mereka ingkar terhadap nikmat Allah, bendungan itu runtuh, menyebabkan banjir besar (sail al-‘arim). Akibatnya, kebun-kebun subur mereka berubah menjadi kebun yang menghasilkan buah pahit (ukulin khamthin), pohon atsar (biasanya diartikan sebagai pohon tamarisk), dan sedikit pohon bidara (sidr).Apakah Buah Mangrove Disebut dalam Ayat Ini?Berdasarkan tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Jalalayn, serta penjelasan ulama, buah yang disebutkan dalam ayat ini adalah:
"Fa a‘radū fa arsalnā ‘alaihim sailal-‘arim wa baddalnāhum bi jannatayhim jannataini dzawātai ukulin khamthin wa aslin wa syai’in min sidrin qalīl."
Terjemahan dalam bahasa Indonesia (Kementerian Agama RI):
"Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon-pohon atsar, dan sedikit pohon bidara."
Ayat ini menceritakan kisah kaum Saba di Yaman yang awalnya hidup makmur dengan dua kebun subur berkat bendungan Ma'rib. Namun, karena mereka ingkar terhadap nikmat Allah, bendungan itu runtuh, menyebabkan banjir besar (sail al-‘arim). Akibatnya, kebun-kebun subur mereka berubah menjadi kebun yang menghasilkan buah pahit (ukulin khamthin), pohon atsar (biasanya diartikan sebagai pohon tamarisk), dan sedikit pohon bidara (sidr).Apakah Buah Mangrove Disebut dalam Ayat Ini?Berdasarkan tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Jalalayn, serta penjelasan ulama, buah yang disebutkan dalam ayat ini adalah:
- Ukulin khamthin: Buah yang pahit, sering diidentifikasi sebagai buah dengan kualitas rendah atau tidak enak dimakan, sebagai kontras dengan buah-buahan lezat dari kebun sebelumnya.
- Pohon atsar: Pohon tamarisk, semak gurun yang buahnya kecil dan pahit, kurang bernilai sebagai pangan.
- Pohon sidr: Pohon bidara, yang menghasilkan buah dengan nilai gizi terbatas dibandingkan buah-buahan subur sebelumnya.



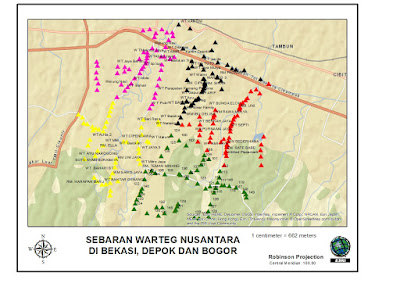
Komentar